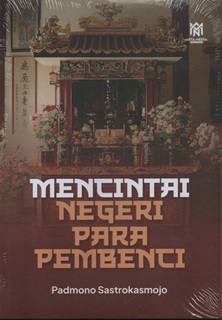Kisah Sofia
Senin, 15 November 2021 07:06 WIB
Seisi Lapas sedang heboh setelah napi transgender yang kecentilan itu ditemukan tewas dengan kepala pecah. Semua orang saling curiga, dan terutama mereka mencurigai aku. Wajar saja, di blok ini, selku termasuk sel isolasi, terpisah dari napi-napi lainnya. Isinya hanya beberapa orang dengan tingkat kejahatan paling berat. Aku salah satu diantaranya.
Makhluk itu mengendap-endap tak sampai dua meter jauhnya dariku. Kepalanya mendongak pongah, kedua matanya mengawasi. Sesekali ia mengeluarkan lidah, menjilat-jilat sembari masih menatapku.
Hmm …
Setelah itu ia mulai menggoyang-goyangkan bokongnya dengan tingkah memuakkan. Khas seorang diva. Seolah dengan begitu, ia ingin mentahbiskan dirinya sebagai salah satu makhluk tereksotis sejagat raya.
Memuakkan.
Aku mengubah posisiku, dari duduk mencangkung menjadi setengah berjongkok. Posisi pelari sprinter sebelum pistol tanda perlombaan ditembakkan. Perlahan kudekati dia, sambil merentangkan tangan.
“Sofia !! Tetap di tempat!”
Tubuhku terpaku di udara. Makhluk sialan itu terkaget sepertiku, kemudian mengeong dan menjauh pergi.
Sipir tinggi besar itu menatapku tajam. “Jangan macem-macem!”
Aku balas menatapnya, tanpa kata. Selama sekian detik kami hanya saling bertatapan. Aku mengangkat kedua telunjuk, membuat beberapa garis imajiner di wajah dan tubuhnya.
“Ngapain kamu?!”.
Aku mendecakkan lidah. “Saya lagi berusaha memetakan berapa banyak potongan tubuhmu jika nanti kamu, saya mutilasi.”
Aku menghabiskan 36 jam berikutnya, di sel hukuman. Sebuah ruangan seukuran 1 x 1 meter, tanpa cahaya matahari.
Dalam gelap, aku terkekeh-kekeh.
***
Rasa penasaran itu pertama muncul di usia 17, saat aku melihat Ella, temanku mengipasi lehernya yang kepanasan. Ia mengangkat dan mengikat rambutnya ke atas tengkuk. Lehernya yang bebas, terpampang di depanku. Beberapa urat kehijauan samar terlihat, sebab kulit Ella putih dan mulus.
Aku menelan ludah.
“Hey! Ngapain ngeliatin?” Ella menggunakan sebuah buku catatan untuk mengipasi tengkuknya. Ia terkikik melihatku. Aku buru-buru menggeleng. Tak mungkin aku katakan padanya, bahwa aku penasaran sekali. Aku ingin mematahkan lehernya yang jenjang itu, untuk melihat apakah ada darah yang bakal keluar.
Esoknya, aku baru tahu bahwa ternyata tidak keluar darah sama sekali.
Ketika tulang belakang leher patah, pembuluh darah arteri vertebralis robek. Ini bisa mengakibatkan kerusakan otak, pingsan, berhenti bernapas kemudian meninggal.
Demikian bunyi potongan artikel yang kemudian kutemukan. Setelah aku mematahkan leher kucing tetangga.
Sampai sekarang, kuburannya masih ada di sudut tanah kosong tempat anak-anak bermain bola. Sebab aku menguburkan mayatnya dengan takzim setelah itu.
Kau mau bilang aku produk gagal? Anak setan? Kesambet iblis karena senang menyiksa binatang? Oh, kau salah besar, kawan.
Aku tumbuh dari dua orangtua lengkap. Ayahku dokter, spesialis bedah forensik, yang sangat dihormati. Ayahku menghabiskan lebih banyak waktunya di ruangan pucat berukuran 6 x 3 meter. Profesi dan keahliannya masih sangat sedikit di negeri ini, membuatnya banyak dipanggil untuk berbagai kasus kejahatan, yang meninggalkan mayat-mayat rusak yang butuh dibedah dan ditelusuri sebab kematiannya.
Ibuku pengurus rumah tangga jempolan. Meskipun ia tidak bekerja, dan hanya seorang ibu rumah tangga, jangan kau bayangkan Ibuku berdaster dan berambut acak-acakan. Ibuku sudah berdandan cantik sejak pukul tujuh pagi. Ia selalu memoles wajahnya dengan cermat, mengenakan pakaian rapi, seolah siap pergi kapan saja. Kalau kau sempat menonton telenovela Meksiko tahun 90-an dan melihat tokoh wanita di dalamnya, yang selalu berdandan rapi, seperti itulah ibuku. Dengan tutur kata lembut khas perempuan ningrat dari Jawa dan sikap tak bercela, Ibuku lambang kesempurnaan seorang wanita.
Mereka menamaiku “Sofia”, artinya kebijakan dalam bahasa Yunani. Sebetulnya, Ibuku yang menamai, ayahku tidak. Ayah kecewa ketika aku lahir sebagai anak perempuan. Lebih kecewa lagi, ketika rahim ibuku terpaksa diangkat setelah pendarahan hebat sewaktu melahirkanku. Itu artinya, menutup kesempatannya untuk mendapatkan anak lelaki.
“Seharusnya kamu itu laki-laki!” begitu kata Ayah, sambil menyesap martini kesukaannya dalam sebuah gelas sloki. Setelah gelas ke-lima, ayah akan tertidur sambil mengorok. Meninggalkanku yang termangu sendirian, antara bosan dan muak karena selalu harus mendengarkan keluhan yang sama.
“Kasihan banget kamu …” Angela menarikku dalam pelukan. Aku bisa mendengar detak jantungnya yang berirama lembut. Saat menceritakan kisah keluargaku ini, kami sedang duduk berdua di kamar kosannya yang sempit.
“Gimana ayahmu, sekarang? Apa sudah menerimamu?” setelah melepaskan pelukannya, Angela menatapku penuh selidik. Kami baru saja bertemu setelah OSPEK fakultas, dan dia menawarkanku untuk tidur di kosannya, daripada pulang ke rumahku yang jauh.
“Yah, masih begitu saja, sih. Untungnya aku ga bodoh-bodoh amat, jadi paling tidak Ayah takkan tambah kecewa,” aku menelan ludah.
“Ibumu?”
“Ibuku yang sempurna itu lari dengan tukang kebun kami, sewaktu aku 10 tahun.”
Angela terkesiap kaget.
Aku tersenyum pahit. “Maaf, aku cerita banyak, padahal ini hari pertama kita bertemu.”
“Gapapa, gapapa. Aku senang kok kamu nginep di sini, jadi ada teman. Kan kita sama-sama mahasiswa baru, harus saling membantu.” Kedua mata Angela berbinar-binar, senyumnya terkembang begitu lebar.
Aku ikut tersenyum.
Esoknya, sebelum subuh, kutinggalkan kosan Angela sambil bersiul riang. Kedua mata Angela yang cantik itu ada di tas ranselku, juga jantungnya yang tadi berdetak lembut.
Itulah pertama kalinya, aku merasa puas. Rasa penasaranku terhadap anatomi manusia terjawab sudah.
Aku terkekeh-kekeh sepanjang jalan menuju panti asuhan.
Oh ya, aku lahir dan tumbuh di panti asuhan. Ayah dokter dan Ibu keren itu, hanya ada di imajinasiku saja.
Oh barangkali di dunia paralel, mereka sungguhan ada. Ah betul.
***
Hampir empat tahun berlalu sejak eksperimenku dengan anatomi manusia dimulai. Di tempatku yang sekarang, sulit sekali untuk melanjutkan eksperimen. Tapi sudahlah, secara garis besar aku sudah tahu semuanya. Tidak perlu susah-susah masuk fakultas kedokteran untuk tahu cara membedah manusia, dan mengetahui letak organ-organ dalamnya.
Setelah percobaan kesekian, aku sudah bosan.
Ya bosan dengan anatomi, ya bosan juga dengan manusia. Seandainya reinkarnasi itu betulan ada, aku ingin diciptakan menjadi makhluk lain selain manusia. Mungkin jadi kecoa yang bisa menyelip ke sudut mana pun, atau lalat yang bisa terbang dan meninggalkan telur di makanan busuk.
Pasti akan menarik, sebab binatang setidaknya hidup tidak ribet. Tak usah susah-susah menerjemahkan apa maunya setiap orang melalui komunikasi verbal dan non verbal. Tak usah repot menanggapi kepala panti yang menyuruhmu rajin mandi, supaya kemudian ia bisa mengintipmu melakukannya. Tak perlu bingung melihat juru masak panti yang senang meludahi makanan yang nantinya dimakan oleh anak-anak se-panti asuhan.
Binatang itu sederhana, manusia rumit, meski sangat predictable, gampang sekali ditebak. Yang mereka pikirkan hanyalah urusan perut, dan di bawah perut.
Seperti sipir tinggi besar yang senang membentakku itu. Dengan tubuhnya yang serupa binaragawati (aku curiga ia mendapat suntikan hormone testosterone), ia akan setia berjalan-jalan mengitari seluruh sel, termasuk lapangan tempat kami berkegiatan setiap hari Senin. Kedua mata kecilnya yang nyalang, mengawasi setiap perempuan yang terpaksa menghabiskan sisa hidup mereka di balik tembok tinggi kompleks lapas ini.
Pun begitu, mungkin hanya aku saja yang tahu apa yang sebenarnya ia incar. Para narapidana perempuan yang baru masuk itu, akan ia suruh mandi di kamar mandi komunal dengan banyak pancuran. Ia akan memerhatikan setiap tubuh polos yang sibuk menggosokkan sabun, untuk kemudian disemprot bedak campur desinfektan, supatya bebas kuman.
Aku tahu napas sipir itu kemudian menjadi ngos-ngosan, keringat bermunculan di dahinya yang sempit. Sama tahunya ketika beberapa napi baru, sering ia seret ke kantornya yang tersembunyi letakknya, di ujung bangunan, berbatasan dengan blok lainnya di lapas ini.
Cih, sangat gampang ditebak. Membosankan.
“Manusia memang membosankan, hahaha.” Kedua mata Juna merah, setelah menenggak beberapa botol minuman berwarna yang ia ambil dari lemari kaca ayahnya. Ia sudah meracau sejak botol kedua, saat ia masih sempat menyelipkan jari jemarinya di balik kemeja tipisku. Memutar-mutar puting dadaku, meremas-remasnya, mencoba membuatku mendesah dan melenguh. Tidak kulakukan, tentu saja. Aku tetap tenang memerhatikannya.
“Seperti ayahku, membosankan hahahaha.” Juna memukul-mukulkan kepalan tangannya ke meja kaca di depan kami. Baginya, segala sesuatu menjadi amat lucu, sekarang.
“Ayahku, yang hakim terhormat itu hahaha. Namanya disanjung sana sini, masuk koran hahaha. Kau tahu Sofia? Di brankas Ayahku, ada tumpukan uang dollar, berlian, surat penting hahaha. Hasil suapan banyak orang hahahaha. Setaaaaaan … hahahaha.”
Aku meraih tas ranselku yang tergeletak di lantai, dekat kaki kami berdua. Juna tentu bermaksud mengajakku senang-senang setelah perkuliahan selesai siang tadi. Mengajakku ke ruang keluarga rumahnya, yang pantas masuk edisi khusus majalah arsitektur ini.
“Ibuku kau tahu? Sosialita kelas kakap, hihihihi. Arisan sana, arisan sini. Hadiahnya brondong, hihihihi.” Juna sekarang terkikik-kikik geli. Tubuhnya terguncang-guncang. Keinginannya menyetubuhiku beberapa jam lalu, agaknya sudah menghilang, berganti dengan racauan yang semakin lama semakin kurang jelas.
Aku mengambil pisau lipatku. Mengelus permukaannya yang licin. Mengamati logo sebuah negara terkenal di Eropa yang tercetak di sana. Jika dikeluarkan, panjang pisau ini takkan lebih panjang dari jengkalan sebelah jariku. Namun, dengan perhitungan presisi dan kekuatan yang tepat, pisau ini bisa dibuat untuk membuat irisan rapi. Aku pernah menggunakannya untuk membuat irisan di perut manusia eksperimenku yang kedua. Cukup satu irisan dengan panjang yang pas, untukku bisa mengintip usus duabelasjari yang panjang dan bergumpal-gumpal seperti sosis itu.
Juna masih meracau, tentang Kakak perempuannya yang menjadi model, tapi juga melacurkan diri demi memenuhi kebutuhannya akan narkoba. Kabarnya, ia menjadi simpanan seorang pengusaha kaya. Pengusaha yang juga sering muncul di tivi, aktif berkegiatan sosial, menyumbang sana sini, macam Sinterklas.
“Lucu sekali keluargaku, ya Sofia hahahaha.” Juna tertawa lagi. Kedua matanya sekarang berair.
“Sekarang, ceritakan tentang keluargamu.” Ia mencoba duduk tegak dengan sisa-sisa tenaga yang ia punya.
“Ga ada,” aku masih menimang-nimang pisau lipatku di tangan.
“Ga ada? Hahahaha.”
“Ya, ga ada. Mungkin pesawat alienku jatuh di ladang jagung, kemudian seekor burung bangau membawaku di paruhnya untuk kemudian diletakkan di pintu depan panti asuhan.” Aku menghunus pisauku. Kilatannya indah, cemerlang.
“Hahaha. Sofia, kamu kok lucu sekali. Hahahaha.”
Selamanya, aku akan merindukan tawa Juna, bahkan setelah kumasukkan semua organ dalamnya ke dalam lemari es, dan kubaringkan ia dengan posisi Vitruvian Man [1]yang terkenal dari Leonardo Da Vinci.
Da Vinci yang jenius itu.
***
Di Lapas tempatku sekarang ini, tak jauh berbeda. Setiap manusianya masih membosankan. Gampang ditebak dan menyedihkan. Maka, sama seperti hidupku sebelumnya, sebelum eksperimen ke-delapanku ketahuan dan aku dijebloskan ke sini, aku tak punya teman seorang pun.
Media menjuluki “gadis jagal abad 21”, memasang fotoku besar-besar di halaman utama. Aku melihatnya dibaca seorang petugas polisi, sewaktu aku masih dalam status penahanan sementara. Petugas yang kemudian selalu tak berani menatap kedua mataku, dan selalu membentak-bentakku, padahal kami terpisahkan jeruji besi berjarak dua meter dari tempatnya berdiri.
Lucu.
Di persidangan, aku menatap tak berkedip puluhan saksi yang dihadirkan. Orang-orang yang mengaku mengenalku, dan menyatakan aku sudah jahat dari awal. Para keluarga korban, guru sekolahku, orang yang satu sekolah denganku, pengurus panti. Aku memandang semuanya tanpa merasa terkesan.
Pengacara yang ditugaskan negara untuk menjadi pembelaku, sudah mewanti-wanti agar aku diam saja. Dasar pengacara murahan! Dari setelan jas yang ia kenakan sampai semua kutipan yang ia bacakan dari KUHP, aku sudah bisa melihat dan menakar kapasitas otaknya. Asal daerah, kuliah hukum di perguruan tinggi negeri, sesekali mendapat beasiswa, dan setelah lulus langsung melamar ke firma besar, dan gagal. Aku tertawa terbahak-bahak ketika merangkai kesimpulan ini di hari pertama pertemuan kami. Ia menatapku tajam, tanpa seulas senyum di wajahnya.
Oh, dia pasti merasa sangat hebat dengan gelar “pengacara”nya itu.
Ya, pengacara murahan itu menyuruhku diam saja selama persidangan. Mana bisa? Sedangkan semua saksi begitu membosankan dan terkadang lucu. Jadi aku sering terbahak-bahak di kursi pesakitanku, dan yang mulia Hakim menatapku penuh kebencian.
Dianggap tidak pernah menyesal setelah membunuh delapan korban dengan cara sadis, Hakim memvonisku hukuman mati. Aku kembali terkikik-kikik geli. Tidak usah pergi jauh-jauh menonton film komedi di bioskop, sebab persidanganku sendiri sangat comical.
Oh, this is so hilarious!
Orang-orang membosankan ini; lahir, makan, minum, buang taik, bercinta, dan menghabiskan siklus hidupnya dengan sekolah-kerja-kawin-beranak yang banyak-kemudian mati, Hahahaha. Sungguh, hidup kecoa jauh lebih menarik.
Mereka berpakaian rapi, dengan semprotan parfum memuakkan dan wajah disetel semenarik mungkin. Mereka menyebutku psikopat, pembunuh berdarah dingin, tanpa sadar bahwa tangan mereka sendiri tidak pernah benar-benar bersih.
Ada pengurus panti yang dulu selalu mendatangi kamarku di tengah malam, menindihku dengan tubuh dewasanya yang berat, mendekap mulutku erat, sambil menuntaskan syahwatnya yang menjijikkan. Ia menyatakan, “Yah, dari kecil terdakwa sudah menunjukkan kecenderungan kejam terhadap semua orang.”
Bajingan!
Seharusnya kucongkel kedua matanya, dan kuputus habis lidahnya yang beracun itu.
Ada guru masa sekolahku, yang kutahu sering nilep uang tabungan anak-anak, dan senang meninggalkan kelas dalam kondisi kosong untuk merokok di lapangan belakang sekolah. Ia bersaksi pernah melihatku menyiksa seekor anak kucing saat waktu istirahat.
Hahahaha. Brengseeeek.
Bukankah seharusnya mereka menyebutku pahlawan. Hey, tak semua orang pantas hidup dan menikmati hidup, aku hanya membantu memuluskan jalan mereka saja. Jika memungkinkan, aku ingin semua orang dibagi dalam banyak kelompok. Kelompok mana yang pantas menjadi manusia, dan mana yang seharusnya dimasukkan ke sebuah kamp konsentrasi kemudian dibom.
Aku masih tertawa terbahak-bahak saat mereka menyeretku ke luar persidangan.
Sungguh dunia sudah dipenuhi banyak badut.
***
Seisi Lapas sedang heboh setelah napi transgender yang kecentilan itu ditemukan tewas dengan kepala pecah. Semua orang saling curiga, dan terutama mereka mencurigai aku. Wajar saja, di blok ini, selku termasuk sel isolasi, terpisah dari napi-napi lainnya. Isinya hanya beberapa orang dengan tingkat kejahatan paling berat. Aku salah satu diantaranya.
Jadi, saat aku melangkah menuju perpustakaan Lapas tempatku biasa bekerja menyusun buku-buku, mereka sibuk berbisik-bisik. Huh! Sekali lihat saja, aku tahu yang membunuh si transgender itu Sulastri. Napi yang selnya berdekatan denganku dan sangat impulsif itu. Dasar bodoh. Aku tak pernah membunuh orang karena tersinggung dengan tindakan dan ucapannya. Aku memilih bahan eksperimenku dengan hati-hati dan penuh perencanaan matang. Ini sih pekerjaan amatir.
Oleh karena itu, aku acuh saja saat Sahira mengajak mengobrol soal ini. Sahira adalah napi yang paling dekat denganku, meskipun tetap tak pernah kuidentikkan ia dengan istilah ‘teman’. Hanya karena seseorang sering bercerita padamu, tidak berarti ia teman bagimu.
Sahira masuk Lapas karena membunuh suaminya yang tukang selingkh, hah! Aku menyipitkan mata saat Sahira bercerita cara ia membunuh suaminya. Jika aku jadi ia, sudah kukeluarkan semua organ suaminya yang tak berguna itu, kemudian kulempar jadi pakan untuk babi hutan. Sisa tubuhnya kubakar dan kusebar abunya ke beberapa toilet bau di seluruh penjuru kota. Itu baru hukuman sesuai. Ah, kreatif dikit, dong!
“Hukumanmu besok, jadi?”
Aku mengangkat kepala dari Animal Farm yang sedang kubaca. Satire George Orwel ini sangat memikat. Sekelompok hewan peternakan yang melakukan kudeta terhadap petani manusia yang menindas mereka. Seperti yang sering kubayangkan terjadi di Lapas ini. Sipir-sipir sombong yang mungkin suatu hari bisa ditaklukan oleh para napi, macam revolusi melawan rezim diktator saja, hahahaha.
“Hukumanmu besok, jadi?” Sahira mengulangi pertanyaannya. Tidak, aku bukan tak mendengarnya. Aku hanya sedang berusaha menyesuaikan frekuensi berpikirku yang tadi sempat terbang melewati tembok tinggi Lapas ini untuk kemudian kembali ke cangkangnya, berupa tubuhku.
“Iya, jadi.” Aku menjawab tak acuh. Sahira terlihat agak sedih. Kenapa? Apakah aku sudah jadi orang spesial baginya?
Kuharap tak seorang pun akan meminta ucapan perpisahan dariku. Untuk apa? Sebab pertemuan dengan mereka pun di luar kuasaku sebagai manusia. Semua terjadi hanya karena keteraturan kosmis saja. Cuih, membosankan.
Esok, di tengah malam aku akan dibawa ke dataran tertinggi di pulau ini. Menghadap ke pantai, sesuai permintaanku. Bukan karena aku ingin melihatnya, tentu saja. Sebab mereka akan menutup kedua mataku di hadapan sekelompok penembak. Bukan, aku hanya ingin mendengar kepak burung camar dan suara debur ombak. Pantai telah menjadi satu-satunya ciptaan entah siapa di galaksi ini, yang kukategorikan sebagai sesuatu yang menyenangkan dan menciptakan rasa nyaman.
“Sofia, tidakkah kamu …”.
“Menyesal? Oh come on Sahira, aku tahu umurku baru menjelang 24 tapi aku tak selugu itu.”
“Seharusnya kamu masih ada di bangku kuliah, mencapai cita-citamu.” Sahira menatapku prihatin.
Aku tertawa.
“Gelar hanya untuk mereka yang masih butuh pengakuan, Sahira. Siklus lahir, hidup, sekolah, kawin, beranak, mati itu untukmu saja. Tidak untukku. I am done with life. At the end of the day, let there be no excuses, no explanations, no regrets.”
Sahira memaksakan senyumnya. Hasilnya fatal, jadi lebih menyerupai seringai tinimbang senyuman.
Di luar kebiasaan, aku meraih tangannya, menggenggamnya erat.
“No regrets Sahira, ingat itu.”
***
Epilog.
Saat mereka menutup kedua mataku, dan regu tembak tinggal mengokang dan menembakkan senjata mereka dalam hitungan detik saja, bibirku menyunggingkan senyum lebar.
Sahira akan baik-baik saja. Kemarin kuselipkan sepotong kertas yang kusobek dari halaman si Animal Farm. Di atasnya sudah kutuliskan nomor kotak PO BOX yang kusewa. Kuncinya kukubur di bawah pohon mangga di halaman panti asuhanku dulu. Sahira sudah tahu ini. Uang yang kudapat dari menguras brankas para korban eksperimenku, bisa ia gunakan untuk membesarkan Amanda, setelah keluar dari sini.
Bagaimana denganku sendiri?
Ah, aku hanya berharap bisa dilahirkan kembali, sebagai kecoa.
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Ares di Ambang Kiamat
Senin, 15 November 2021 08:34 WIB
My Imagination
Senin, 15 November 2021 08:28 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0








 98
98 0
0
 Berita Pilihan
Berita Pilihan